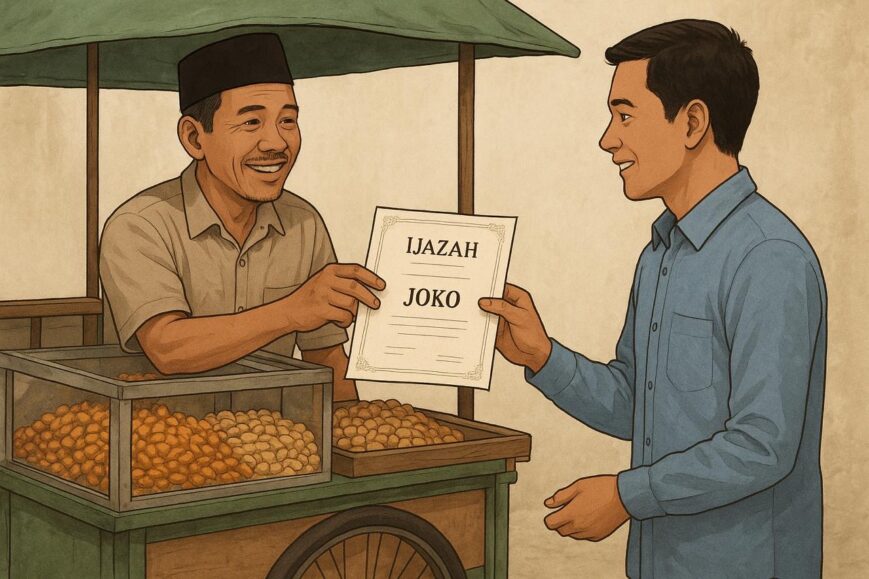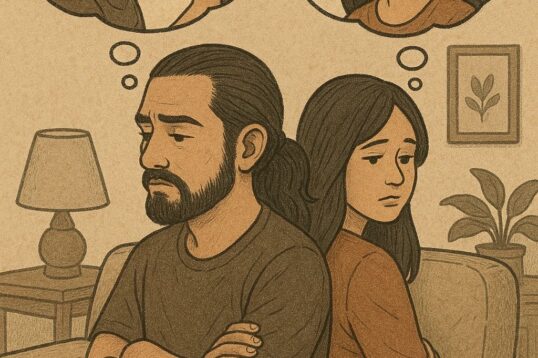Semua memang bermula dari Tapis. Ketika peradaban masyarakat Lampung di masa lampau yang sedemikian tinggi, kebutuhan simbolisasi menjadi mutlak, ini pula berlaku untuk norma sekaligus status sosial. Seperti Tapis, kebutuhan eksistensi produk budaya pun berkembang, menjadi sulam usus hingga kemudian sulam Jalin Kepang yang rumit, tapi justru menjadi jembatan tradisi yang terus (diupayakan) melestari.
(Lontar.co): Paviliun salah satu rumah di Gunungsugih itu, sekilas terlihat lengang. Padahal, sedang ada lima perempuan paruh baya yang terus saja terpaku pada bidang-bidang lembar kain di tangan mereka.
Pada kain-kain dengan warna yang cenderung merah itu, pola-pola geometris begitu kuat, meski dikerjakan dengan tangan, tapi detailnya terjaga, orisinalitasnya juga makin terasa.
Hari itu, seperti biasa, hampir setiap pekannya, menyulam memang menjadi rutinitas baru yang meneduhkan buat sejumlah perempuan di Gunungsugih, utamanya mereka yang paruh baya. Ini bukan sekedar intermezzo, tapi menjadi aktivitas yang selalu pasti mereka kerjakan di kala luang.
Momen mereka seperti mengingatkan periode lampau, perempuan-perempuan adat Lampung Pepadun yang bekerja di sektor-sektor domestik, di bawah sistem sosial patriarki, yang justru direspon dengan kreativitas yang apik pada perempuan-perempuan Lampung di kala itu.
Setelah Tapis, naluri kemudian menuntut pergeseran kebutuhan, bahwa tubuh perempuan harus terlindungi dan tertutup, tapi juga harus hadir sebagai simbol melalui nilai estetis, pada fase itu, perempuan-perempuan Lampung memang mendapat tempat paling istimewa, mereka menjadi sebuah bagian penting dari harga diri (pi’il) tiap lelaki Lampung, sebagai entitas yang harus dilindungi sekaligus dijaga.
Kebutuhan ini yang kemudian diterjemahkan dengan hadirnya sulam usus, tapi, ia bukan cuma berfungsi sebagai bebe (penutup bagian dada), selepai atau penutup siger pada pakaian adat pengantin perempuan, maknanya lebih luas, cenderung filosofis, tiap detailnya juga menandakan status sosial yang tinggi, karena penggunaannya tak bisa sembarangan.
Kala itu, masyarakat adat Lampung sudah memiliki khasanah budaya yang mapan, sifatnya yang terbuka, membuat proses akulturasi budaya terasa lebih lempang. Jalurnya, melalui perdagangan, dan kontak-kontak sosial lain yang lebih hidup.
Pada proses ini kemudian, masyarakat Lampung utamanya kaum perempuan, belajar dalam banyak hal, meski ikatan patriarki secara tak langsung membatasi gerak mereka, justru pada masa ini perempuan-perempuan Lampung dituntut untuk mempelajari tiap detailnya dengan amat cepat.
Pada periode ini, kaum perempuan Lampung berada pada fase kreativitas yang luar biasa, mereka mempelajari tiap detail produk kebudayaan meski hanya dalam momen yang terbatas.
Salah satunya adalah sulam usus, produk kerajinan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kain Tapis ini, memasuki masa keemasannya di abad ke 16, keberhasilan pengrajin-pengrajin sulam usus kala itu bahkan mendapat apresiasi luar biasa, status sosial mereka juga terangkat, karena sebagai produk budaya yang eksklusif, tak banyak orang bisa membuat sulam usus, apalagi dengan bahan baku yang serba terbatas kala itu, karenanya sebagaimana pembuatnya, sulam usus menjadi khasanah wastra masyarakat Lampung setelah Tapis.
Sampai kini, sulam usus sebenarnya masih tetap ada, meski ditepikan oleh perkembangan zaman, ia lestari meski tersuruk-suruk di kampung-kampung, di tangan-tangan yang sudah semakin keriput oleh usia.
Pada gilirannya, waktu kemudian mengasah kreativitas baru pada perempuan Lampung di masa di mana, akulturasi budaya menjadi semakin mudah.
Sulam Usus yang lahir dari sejumlah percampuran budaya multietnis yang kaya, termasuk unsur-unsur ke-lampung-an yang tak kalah dominan, kemudian melahirkan konsep baru yang menandai bahwa kebudayaan pada masyarakat Lampung sejatinya tak pernah luntur, ia hidup dalam memori setiap orang, yang kemudian melahirkan Sulam Jalin Kepang, sebagai identitas baru sekaligus turunan dari sulam usus.
Sebagai produk yang tak bisa dilepaskan dari sulam usus, sulam Jalin Kepang justru lahir di Lampung Tengah, sementara sulam usus awalnya lahir dari proses kreativitas kaum perempuan di Tulangbawang, tapi jika ditarik garis lurus, Tulangbawang dan Lampung Tengah adalah bagian dari kelompok besar masyarakat Lampung Pepadun.
Dari sini, sulam usus tidak hanya dipertahankan sebagai peninggalan budaya, tetapi juga bertransformasi menjadi produk-produk kontemporer yang menarik, ia seperti menjembatani tradisi dengan selera modern.
Sebagai produk hasil transformasi tradisi, sulam Jalin Kepang memang merevitalisasi kekayaan seni tradisinya.
Pengembangan produk budaya wastra ini, tidak hanya terpaku pada inovasi motif semata.
Lebih dari itu, proses ini secara teknis melibatkan upaya mengangkat nilai-nilai kebudayaan lokal yang kaya dan mendalam yang di simbolisasi melalui pola-pola geometris yang baku, sebenarnya ini bukan bentuk kekakuan, tapi justru menjadi penanda bahwa, pola yang terkonsentrasi pada satu jenis, pada akhirnya bisa dikembangkan dalam banyak motif.
Nilai-nilai budaya ini yang kemudian dikutip ulang dalam bentuk visual dan sandang sekaligus, dengan mempertimbangkan aspek estetika yang matang.
Pada fase ini, sulam Jalin Kepang tidak hanya ingin memastikan bahwa setiap karya tidak hanya elok untuk dipandang, tetapi juga sarat makna dan merepresentasikan identitas budaya yang kuat, menciptakan jembatan antara masa lalu dan masa kini, yang apik.
Sebagai bagian dari produk budaya, Jalin Kepang memiliki proses dengan karakter pengerjaan yang sangat rumit dan detail. Prosesnya bahkan membutuhkan kesabaran luar biasa, serta waktu penyelesaian yang cukup lama, ketelitian menjadi sebuah keniscayaan.
Secara logis, semakin tinggi tingkat kesulitan motif, maka semakin tinggi nilainya, karena ada ketelitian sekaligus dedikasi yang besar di dalamnya.
Kini, sulam Jalin Kepang bukan hanya produk transformasi tradisi, tapi juga menjadi bagian identitas kultural masyarakat pepadun yang ada di Lampung Tengah.
Teknik pembuatan hingga mempertahankan motif maupun pola yang asli bukan hanya menjadi upaya memperjuangkan kelangsungan kain wastra ini, tapi juga menjaga agar produk budaya ini tetap relevan di masa ini.
Tak banyak yang punya peran sentral dalam pembuatan sulam Jalin Kepang ini, apalagi yang masih menjaga betul orisinalitas motif pada sulam Jalin Kepang agar tak keluar pakem dari sulam usus itu sendiri.
Salah satunya adalah Maidah. Perannya di teknik sulam Jalin Kepang ini amat sentral, karena ia tidak hanya menguasai teknik dan pengetahuan mendalam tentang kerajinan ini, tetapi juga aktif dalam upaya pelestarian dan pengembangannya di komunitas.
Kiprahnya tak pendek. Ia terus meregenerasi sulam Jalin Kepang agar bisa lestari dan terus ada.
Semangatnya itu pula yang kemudian membawa teknik sulam Jalin kepang ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, beberapa waktu lalu.
Meski dianggap sebagai warisan budaya takbenda yang dianggap bersifat abstrak, sulam Jalin Kepang menjadi sebuah identitas tentang kekayaan luhur tradisi masyarakat Lampung, utamanya kaum perempuan Lampung yang tak hanya bergumul dalam pekerjaan domestik, tapi juga mengembangkan visi identitas keperempuanan Lampung yang peradabannya sudah amat maju, yang tak hanya bicara soal kebutuhan sandang semata, tapi juga tentang nilai-nilai estetis.