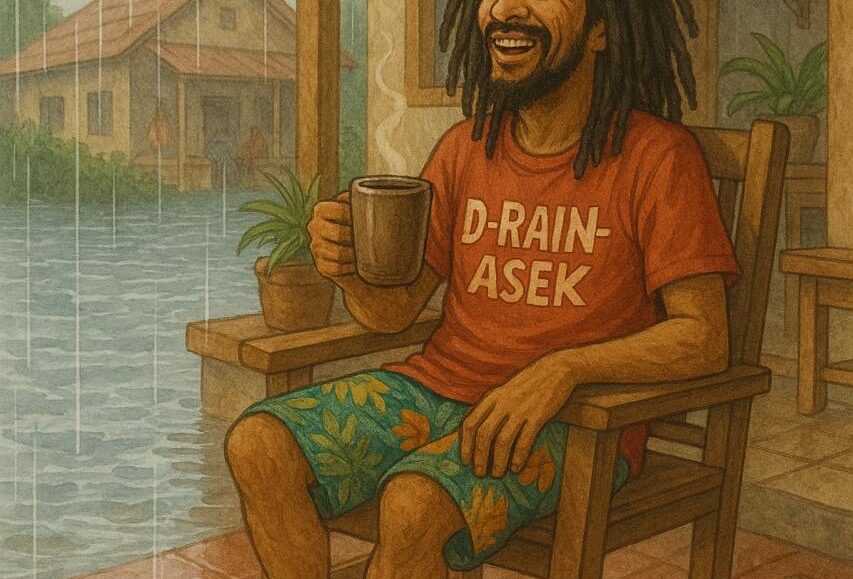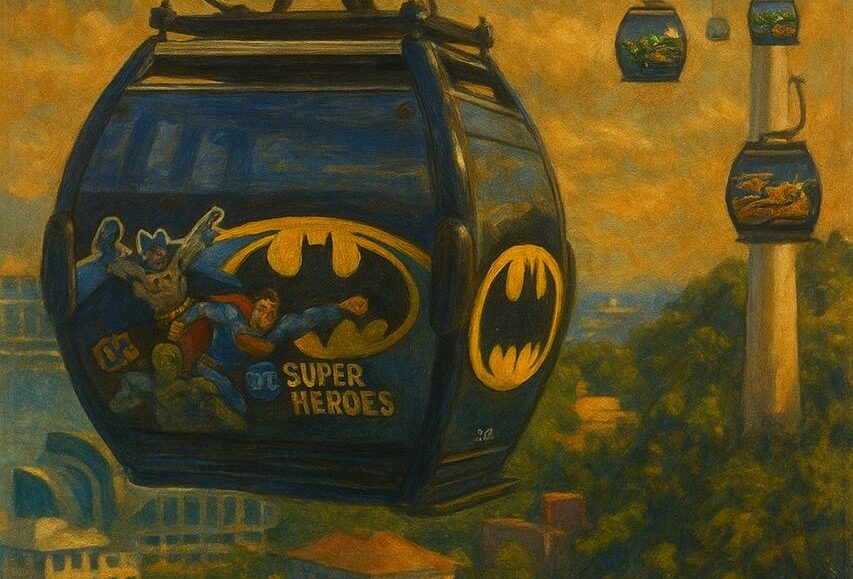Petugas pemadam kebakaran (Damkar) menjinakkan kobaran api, itu biasa. Meski, tak jarang nyawa taruhannya, lah memang sudah risiko tugas. Yang keren itu ketika mereka “mau-maunya” ngurusin sarang tawon di rumah warga. Sempet-sempetnya bantu lepasin cincin emak-emak yang saking kenceng meluk jari manis akhirnya tak bisa dicopot. Lho, sejak kapan petugas Damkar jadi semacam rescue palugada (apa lu mau, gue ada)?
(Lontar.co): Ternyata markas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bandarlampung yang berada di Jl. Kapten Tendean, Tanjungkarang Pusat, punya dua bidang tugas utama. Pertama Bidang Pemadaman Kebakaran berikutnya Bidang Penyelamatan. Nah, urusan tawon dan melepas cincin itu menjadi tupoksi bidang yang disebut belakangan.
“Siapa bilang kami tak takut tawon. Tetap ada rasa takut itu. Kami kan bukan Superman,” seloroh Komandan Pleton (Danton) Ifan Afandi kepada Lontar.co, saat menceritakan pengalaman mereka menangani sarang tawon yang kerap dikeluhkan warga, Kamis (10/7/2025).
Apalagi, imbuh dia, kalau tawon yang ditangani berjenis Ndas atau biasa disebut tawon Vespa Affilis. Ini tergolong tawon ganas. Sekali kena sengat dipastikan bakal demam. “Rekan-rekan di sini banyak juga yang pernah nyicipin kena sengat. Tapi mau gimana lagi. Bagi kami ngurusuin yang kayak begitu sudah jadi makanan sehari-hari,” terangnya.

Berbekal teori dan pengalaman di lapangan, sambungnya, petugas akhirnya menemukan teknik efektif untuk menanggulangi sarang tawon yang biasa muncul di pohon atau rumah kosong yang berada di permukiman warga.
“Kejadian baru-baru ini, misalnya, kami tangani sarang tawon di rumah warga di Sukarame. Jenisnya tawon Vespa Affilis,” kata Ifan. Karena titik lokasinya di atas dan agak sulit dijangkau, kisahnya, akhirnya diputuskan memusnahkan sarang tawon dengan teknik brangas.
Secara umum teknik ini berupa penyemprotan cairan pembasmi serangga yang dicampur air dan deterjen ke sarang tawon. Kemudian dilanjutkan dengan pembakaran atau pengemasan sarang tawon. Tujuannya untuk membunuh tawon dan meminimalkan risiko sengatan bagi petugas dan warga sekitar.
“Kalau letak sarangnya mudah dijangkau, biasanya kami menutup pintu atau lubang yang dipakai tawon untuk masuk dan ke luar sarang. Lubang itu disumpal pakai kapas yang sudah direndam bensin. Setelah itu baru dibakar dengan alat khusus yang mengeluarkan api dalam tekanan besar,” urai Ifan.
Ditambahkan Krisna Laksamana, selaku Kabid Penyelamatan, tugas mereka tak berhenti sebatas mengurusi sarang tawon. Bahkan, petugas kerapkali turun tangan merespon permintaan warga untuk bantu mengeluarkan kunci yang tertinggal di bawah jok motor.
“Ya tetap harus kita respon. Biasanya anak kost yang sering bermasalah dengan kunci,” ucap Krisna seraya tersenyum. Dalam kasus serupa ini, terang dia, penanganannya dicoba membuka jok motor dengan alat yang mereka punya.
Kalau masih tidak berhasil, atas izin pemilik kendaraan, biasanya akan diambil langkah terakhir lewat membuka paksa. “Untung, umumnya bisa diatasi tanpa buka paksa,” kata Krisna yang mendampingi Sekretaris Damkar, Ahmad Husni.
Lebih lanjut Ahmad Husni menerangkan, di Bidang Pemadaman, pihaknya diperkuat oleh 30 personil serta 22 unit mobil Damkar. Setiap unit berisikan 4 sampai 6 personil yang dilengkapi alat pelindung diri atau APD.

“Mengingat Bandarlampung terus berkembang, sekarang malah sudah layak disebut kota besar, kami berharap bisa didukung APD yang lebih memadai. Karena sangat penting untuk mendukung tugas, sekaligus menjamin keselamatan petugas di lapangan yang berpotensi risiko tinggi,” harap Husni.
Sebuah permintaan tak berlebihan kiranya, mengingat petugas Damkar yang punya selogan “Pantang Pulang Sebelum Padam” ini, memang harus bisa dijamin keselamatannya agar benar-benar bisa pulang ke rumah dalam keadaan sehat wal’afiat. (*)