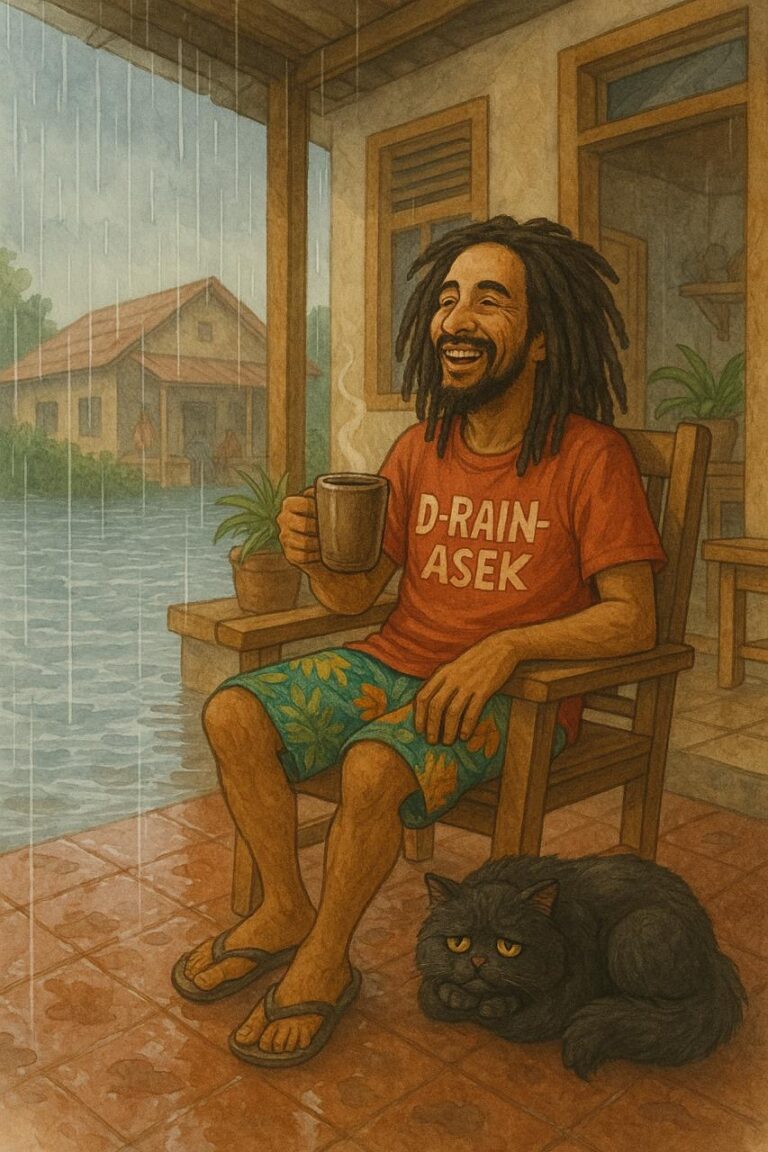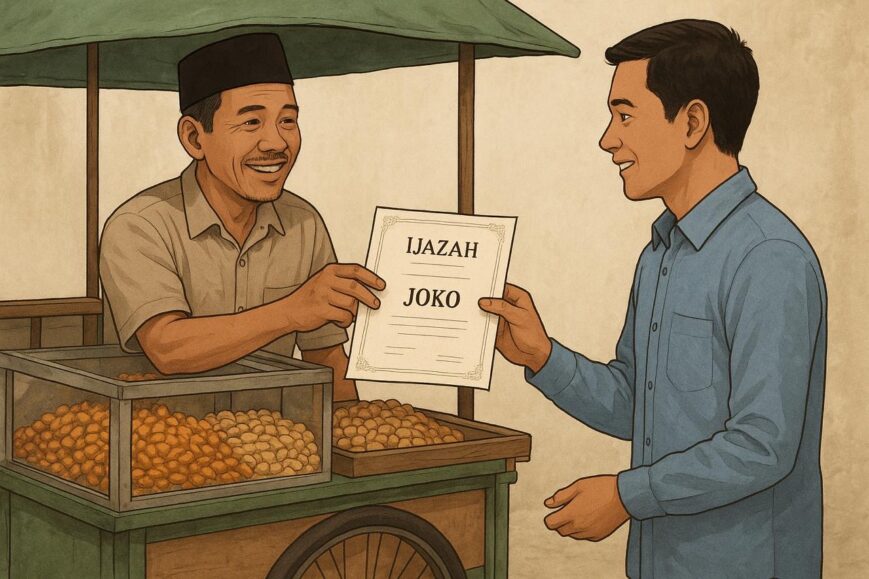Bank Dunia menyebut angka kemiskinan Indonesia melonjak jadi 194,6 juta jiwa. Angka ini, selisih jauh jika membandingkan data statistik angka kemiskinan versi BPS per September 2024 yang hanya 24,06 juta jiwa, Komparasi ini bakal terlihat lebih njomplang jika mengukur angka tahun 2025 nanti; daya beli yang melemah hingga PHK massal dimana-mana. BPS cuma ABS?
(Lontar.co): Bekerja sebagai driver ojek online sejak dua tahun terakhir membuat Handoko harus ekstra keras mencari uang. Ia terpaksa bekerja sejak pukul 6.00 pagi hingga malam hari, tak jarang ia juga harus onbid hingga dini hari, jika penghasilan yang ia dapat belum memadai.
Sebagai driver ojol, rata-rata Handoko hanya bisa membawa pulang uang tak sampai Rp100 ribu, setelah dipotong untuk membeli BBM dan top up saldo drivernya.
Dengan uang seminim itu, ia harus bisa menghidupi istri dan dua anaknya yang masih kecil, dan menyisihkan setidaknya Rp20 ribu per hari untuk angsuran motor bulanannya.
Praktis, ia dan keluarganya harus hidup dengan uang Rp80 ribu per hari. Uang ini dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang harganya terus melambung.
Ia dan istrinya terpaksa mengalah, makan seadanya, demi agar kedua anaknya bisa tumbuh seperti anak-anak kebanyakan.
“Sekarang harga beras aja sudah 20 ribu sekilo. Beras sekilo itu, cuma cukup untuk dua hari. Itu baru beras, belum lauknya. Terpaksa kami yang mengalah, makan seadanya, prioritasnya buat anak-anak aja,” katanya.
Terkadang, demi bisa mendahulukan kebutuhan pangan anak-anaknya, Handoko dan istrinya hanya mengkonsumsi mie instan.
Idealnya, menurut Handoko, untuk menghidupi keluarganya, ia butuh uang paling sedikit Rp150 ribu per hari. Dengan uang sejumlah itu, setidaknya kebutuhan pangan keluarganya bisa tercukupi walau sederhana.
Berbeda dengan Handoko, Ardianto buruh bangunan yang juga warga Desa Pemanggilan, Natar terpaksa harus bekerja apa saja demi mencukupi kebutuhan keluarga.
Apalagi, sejak awal Januari 2025 lalu, ia sudah menganggur, mau tak mau ia dan istrinya harus banting tulang kerja serabutan.
Ardianto kini bekerja sebagai pekerja harian di toko material, dengan upah Rp50 ribu sehari, sembari terus was-was jika tenaganya tak dipakai lagi.
Sedang istrinya ikut bekerja sebagai buruh pembuat bata dengan bayaran kurang dari Rp25 ribu sehari—tergantung dari jumlah bata yang ia buat.
Itu pun mereka harus bekerja dari pagi hingga sore.
Ketiga anaknya juga dipaksa menyesuaikan keadaan orang tuanya, terlebih mereka juga tak terdata sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.
“Kalau nggak makan sehari dua hari itu sudah biasa, apalagi cuma makan pakai sayur daun katuk,” katanya.
Buatnya, kebutuhan hidup bukan cuma soal makan, apalagi anak-anaknya sudah mulai besar, mau tak mau ada prioritas lain yang harus mereka dahulukan,”dua anak saya mau masuk sekolah, semuanya butuh biaya, kerjaan saya nggak nentu apalagi istri, jadi terpaksa di hemat-hemat sebisanya”.
Untuk dirinya, istri dan ketiga anaknya yang sudah beranjak besar, Ardianto menyebut butuh paling sedikit Rp200 ribu per hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, selain untuk membeli beras, lauk pauk, ia juga butuh untuk biaya sekolah kedua anaknya.
“Istri itu, kalau ke pasar bawa uang Rp50 ribu, cuma dapat beras dua liter sama sayur-sayuran aja, kalau dipakai beli ikan atau telur itu, sudah nggak cukup uangnya”.
Perlambatan ekonomi yang memicu terjadinya PHK massal juga amat mempengaruhi keadaan sebagian besar masyarakat saat ini.
Serapan kebutuhan yang rendah di sejumlah pasar menjadi indikator, daya beli masyarakat yang cenderung menurun drastis sejak awal 2025.
Tak hanya retail yang terdampak, pedagang-pedagang di pasar tradisional pun ikut merasakan.
Pada hari raya kurban lalu misalnya, nilai transaksi yang diharapkan meningkat justru sebaliknya.
Tren itu juga bahkan sudah terlihat sejak sepekan sebelum hari raya Idul Fitri 2025, pada Maret lalu, konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan pokok cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Parahnya, hal ini bahkan sudah diprediksi oleh Bank Dunia dalam laporan Poverty and Inequality Platform.
Bank Dunia meratifikasi acuan standar garis kemiskinan secara global—termasuk Indonesia, dari paritas daya beli (PPP) tahun 2017 ke PPP 2021.
Dalam purchasing power parity (PPP) 2021 ambang garis kemiskinan mengalami peningkatan untuk semua kategori negara berdasarkan pendapatannya.
Negara dengan pendapatan menengah ke bawah (lower-middle income) standarnya berubah dari $3,65 per hari jadi $4,20 per hari.
Sedang Indonesia yang masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income) standar batasnya juga naik dari $6,85 menjadi $8,40 per hari.
Jika ‘dikurs-kan’ dalam rupiah, standar $1 PPP sama dengan Rp5.993.
Purchasing power parity (PPP) adalah konsep standar dasar yang dipakai oleh Bank Dunia untuk membandingkan harga barang dan jasa yang sama di seluruh negara yang kemudian dikonversi melalui nilai mata uang dollar Amerika, agar proses perbandingan lebih mudah dilakukan.
Dengan metode itu, maka terdapat sebanyak 194 juta lebih penduduk Indonesia—dari total sebanyak 285 juta penduduk Indonesia tahun 2024, yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan pengeluaran rata-rata per hari di bawah Rp49.244.
Kenyataannya, rumus penghitungan standar garis kemiskinan versi Bank Dunia ini jauh lebih relevan dengan kondisi Indonesia kini, melalui sejumlah indikator yang menggejala saat ini.
Termasuk keadaan ekonomi yang dialami oleh Handoko dan Ardianto, jika merujuk standar PPP Bank Dunia, mereka adalah bagian dari 194 juta penduduk miskin Indonesia.
Bandingkan dengan standar garis kemiskinan acuan BPS yang masih mengklasifikasikan pengeluaran di bawah Rp20 ribu per hari baru bisa disebut sebagai penduduk miskin.
Faktanya, dengan uang Rp20 ribu sekalipun, masih belum cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup satu keluarga, bahkan keluarga dengan satu anak sekalipun!.
“Beras aja sudah Rp20 ribu sekilo, terus makannya nggak pake lauk begitu? Atau nggak ada kebutuhan yang lain? Orang hidup itu butuh biaya buat hidup, apalagi punya anak dan istri,” tutur Handoko.
Selama ini, sejak tahun 1998 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasi penduduk miskin dengan pengeluaran di bawah Rp595.242 ribu per bulan yang jika dibagi per hari menjadi sekitar Rp20 ribu pengeluaran per hari.
Standar BPS ini jelas tak aplikatif dengan keadaan saat ini.
Pemerintah jelas sudah abai dengan rakyatnya, karena menerapkan aturan tak sesuai dengan reflektivitas keadaan, bayangkan aturan yang diberlakukan pasca orde baru tumbang masih dipakai sampai kini, yang rentang jaraknya hampir mendekati tiga dekade dengan beragam perubahan ekonomi, pola konsumsi, kebutuhan dan pasar yang dinamis hanya dalam hitungan hari.
Difrensiasi standar kemiskinan ini tak ayal memicu tendensi negatif; BPS malas, sementara yang lain menyebut BPS cuma ABS.
Tindakan yang disadari atau tidak oleh BPS ini juga mengarah pada ‘kejahatan kemanusiaan’, karena pemerintah jelas amat tergantung pada statistika badan itu dalam hal pendistribusian bantuan, me-regulasi ekonomi dan pengambilan kebijakan lain yang bersentuhan langsung dengan mereka-mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Ditengah ketidakpercayaan publik terhadap metodologi standar kemiskinan BPS, mereka justru berdalih perbedaan standar angka kemiskinan dengan Bank Dunia, lebih disebabkan karena penentuan median garis kemiskinan berdasarkan pendapatan menengah-atas bukan penghitungan penduduk Indonesia yang lebih spesifik.
Dalam menetapkan standar miskin dengan pengeluaran per kapita Rp20 ribu sehari, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, yang dibagi dalam dua komponen utama; makanan dan non makanan.
Untuk komponen makanan sebagai komponen utama, BPS menerapkan prinsip standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari dalam satu kesatuan pangan lengkap meliputi; beras, lauk (telur, tempe, tahu, sayur dan minyak goreng).
Urusan makin njlimet mana kala BPS juga menyebut rumus penghitungan angka kemiskinan di tiap daerah juga berbeda-beda, tapi anehnya dengan berbagai alasan itu, BPS tetap menetapkan standar kemiskinan nasional Rp20 ribu per hari per kapita atau Rp595.242 per bulan per kapita.
Dengan segala kompleksitasnya, metodologi penghitungan standar kemiskinan yang dipakai BPS jelas sudah usang, jadoel dan tak relevan dengan kondisi dan pola konsumsi, apalagi selama 27 tahun lebih metodologi itu tak ada perubahan sedikitpun.
Penghitungan biaya kebutuhan dasar (cost basic needs) meski masih relevan dipakai, tapi perlu diupdate secara berkala dengan mengamati pergeseran pola-pola konsumsi yang terjadi di masyarakat dan pasar, karena kecenderungan pergeseran itu bergerak makin kompleks, disitulah peran dan kerja BPS sebenarnya.
Lucunya, BPS mengesankan seperti bekerja dengan kacamata kuda, tak pernah peduli dengan tren, pola konsumsi, pasar hingga kebutuhan hidup yang selalu dinamis.
“Dengan Rp20 ribu sehari, orang atau keluarga Indonesia itu memang masih bisa hidup, tapi hutang sana-sini,” ujar pengamat ekonomi dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana.
Ada kesan lain, lanjutnya, jika standar kemiskinan berubah, bakal merusak citra pemerintah selama ini yang dianggap sukses menekan kemiskinan, sementara fakta sesungguhnya justru berkata lain.
“Ini bisa berdampak pada prestasi dari pemerintah yang buruk karena tak berhasil menekan angka kemiskinan, malah sebaliknya semakin tinggi”.
BPS yang selama ini dianggap sumber kredibel dengan data statistik superior ternyata selama ini bermain dalam data yang monoton, tak kredibel dan terus memperburuk keadaan.
Untuk hal yang mendasar, dalam hal hajat hidup masyarakat banyak dan kebanyakan BPS sedemikian ‘tega’ membangun kesan yang kontradiktif dengan keadaan sesungguhnya.
Selama 27 tahun, keadaan dibuat samar, dalam komposisi statistik tanpa akurasi lapangan yang kuat, eksistensi BPS memang patut dipertanyakan (.)